Ada sesuatu yang unik sekaligus mengerikan dari gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia pada akhir Agustus 2025. Awalnya, publik turun ke jalan untuk menolak kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal—Rp 50 juta per bulan untuk perumahan, atau sepuluh kali lipat UMR Jakarta. Namun, yang terjadi kemudian jauh lebih radikal: rumah-rumah anggota dewan diserbu dan dijarah massa.
Eko Patrio, Ahmad Sahroni, hingga Uya Kuya, merasakan langsung bagaimana kemewahan pribadi mereka menjadi sasaran kemarahan publik. Bahkan rumah Sri Mulyani, yang dikenal sebagai teknokrat, ikut tak luput dari amuk massa. Tentu saja penjarahan tidak bisa dilegalkan, tapi peristiwa ini menyimpan pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar aksi kriminal.
Mengapa rakyat sampai sefrustrasi itu? Jawabannya sederhana: kesombongan politik. Ahmad Sahroni, misalnya, dengan enteng menyebut pengkritiknya sebagai “orang tertolol sedunia.” Ucapan semacam ini ibarat bensin yang disiram ke api. Saat politisi tampil arogan, publik merasa bukan hanya diabaikan, tetapi juga dihina. Akumulasi kekecewaan akhirnya menemukan jalannya dalam bentuk perlawanan paling ekstrem: mendobrak pagar rumah dan merampas harta wakil rakyat.
Sosiolog Nike Kusumawanti menyebut fenomena ini sebagai kegagalan komunikasi demokratis. Teori Habermas menjelaskan, demokrasi hanya sehat jika ada komunikasi rasional antara rakyat dan wakilnya. Ketika yang terjadi justru komunikasi strategis—elit sibuk melanggengkan privilese—rakyat merasa teralienasi. Inilah yang oleh Marx disebut alienasi ganda: wakil rakyat bukan lagi representasi, melainkan simbol keterputusan.
Dalam kerangka itu, penjarahan bukan sekadar kriminalitas, tetapi ritual simbolik. Barang-barang mewah yang dibawa keluar dari rumah politisi dipandang sebagai “hak rakyat” yang selama ini dirampas oleh kebijakan elitis. Teriakan “terima kasih” massa saat menjarah rumah Eko Patrio menunjukkan betapa penjarahan diperlakukan sebagai bentuk balas dendam sosial, bukan sekadar pencurian.
Namun, kita tentu tidak bisa merayakan anarki. Kekerasan yang dilegalkan hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan baru. Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga tak bisa sekadar menuding massa sebagai perusuh. Sebab, di balik peristiwa itu ada kritik keras yang nyata: demokrasi kita sedang sakit. Warga merasa tak didengar, lalu memilih cara paling kasar untuk membuat penguasa menoleh.
Bagi saya, peristiwa ini adalah peringatan. Ketika suara rakyat dibungkam oleh arogansi elit, maka rakyat akan berbicara dengan caranya sendiri—meski lewat cara yang destruktif. Penjarahan rumah politisi adalah alarm keras yang mestinya membuat penguasa terbangun: bahwa demokrasi tidak bisa bertahan hanya dengan prosedur, melainkan harus dijaga dengan rasa keadilan.
Jika pesan ini lagi-lagi diabaikan, jangan kaget bila gelombang amarah rakyat berikutnya datang lebih besar, lebih liar, dan lebih sulit dikendalikan.
istimewa







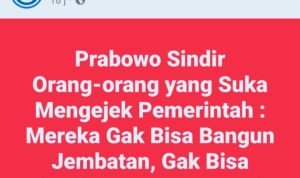
Komentar