Oleh: Dr Fairus M Nur Ibrahim MA, Dosen Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Istilah “bom waktu MBG” terdengar keras, bahkan provokatif. Namun, justru di situlah letak relevansinya. Dalam urusan pangan dan gizi, dampak paling berbahaya tidak selalu meledak seketika. Ia bekerja diam-diam, menumpuk, lalu meledak jauh di kemudian hari. Hari ini Indonesia sedang menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan: anak sekolah dan remaja mulai terserang penyakit yang dahulu identik dengan usia lanjut—gagal ginjal, obesitas, diabetes, gangguan metabolik, hingga penyakit hati. Akar persoalannya relatif jelas: pola makan yang dipenuhi makanan ultra-proses, sarat gula, garam, lemak, dan zat aditif.
Di tengah situasi genting itulah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Secara konsep, ini adalah kebijakan yang mulia dan sangat dibutuhkan, sekaligus realisasi janji politik Prabowo–Gibran. MBG bukan sekadar program pendidikan atau kesehatan, melainkan kebijakan pangan nasional yang menyentuh gizi, sumber daya manusia, ekonomi lokal, dan masa depan generasi bangsa. Melalui MBG, anak-anak dari keluarga rentan dijanjikan akses makan yang layak.
Namun, justru karena skalanya masif dan cakupannya nasional, MBG tidak boleh salah arah. Kesalahan kecil pada standar menu, bahan baku, atau filosofi gizi bisa berdampak besar dan panjang. Di titik inilah MBG berpotensi berubah dari program mulia menjadi bom waktu.
Reduksi Makna Gizi
Bom waktu pertama lahir dari cara pandang yang keliru terhadap gizi. Jika gizi direduksi menjadi sekadar hitungan kalori dan daftar zat gizi di atas kertas, maka makanan ultra-proses dengan mudah lolos sebagai menu “bergizi”. Nugget, sosis, mi instan, minuman berpemanis, atau produk fortifikasi bisa saja tercatat mengandung protein, vitamin, dan mineral.
Padahal tubuh anak bukan mesin akuntansi. Ia merespons kualitas bahan, tingkat pemrosesan, dan keseimbangan nutrisi alami. Makanan yang terlalu sering diproses justru berisiko mengacaukan sistem metabolisme yang masih berkembang. Berbagai riset internasional telah lama memperingatkan bahaya konsumsi makanan ultra-proses secara rutin—fakta yang sebenarnya mudah ditemukan dan dipahami.
Normalisasi Selera yang Keliru
Bom waktu berikutnya adalah pembentukan selera. Apa yang dimakan anak hari ini akan membentuk preferensi makannya di masa depan. Jika MBG membiasakan rasa gurih buatan, manis berlebih, dan tekstur instan, maka itulah standar rasa yang akan mereka cari kelak. Sayur segar dianggap hambar, ikan dinilai amis, dan makanan rumahan terasa “tidak enak”. Ini bukan soal selera semata, melainkan soal kegagalan menanamkan budaya pangan sehat dalam jangka panjang.
Beban Negara yang Tertunda
Bom waktu ketiga berkaitan dengan beban fiskal. MBG kerap dilihat sebagai pengeluaran besar negara. Namun, jika salah desain, biaya sesungguhnya justru muncul di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan buruk berisiko menjadi warga negara dengan ongkos kesehatan tinggi. Anggaran kesehatan akan terkuras untuk menangani penyakit tidak menular yang seharusnya bisa dicegah sejak usia sekolah. Negara pun membayar dua kali: hari ini untuk makan, esok untuk pengobatan.
Ilusi Keberhasilan
Ada pula bom waktu berupa ilusi sukses kebijakan. Secara administratif, MBG bisa tampak berhasil: jutaan porsi tersalurkan, laporan rapi, foto-foto anak makan dari kotak MBG beredar di media. Namun kesehatan tidak tunduk pada laporan tahunan atau pidato pejabat. Ia diuji oleh waktu—oleh kondisi metabolik anak, kebiasaan makan, dan kesehatan organ mereka. Tanpa indikator kualitas jangka panjang, keberhasilan MBG bisa menjadi semu.
Pentingnya Kontrol Sosial
Karena itu, pengawalan publik menjadi kunci. Orang tua, guru, akademisi, dan masyarakat sipil perlu berani bertanya: apa isi menu MBG hari ini? Dari mana bahannya? Seberapa tinggi tingkat pemrosesannya? Apakah anak dikenalkan pada pangan segar, atau sekadar versi “lebih rapi” dari jajanan pabrikan?
Selama ini, orang tua dan sekolah kerap diposisikan sebagai penonton pasif. Padahal, merekalah aktor paling strategis dalam melakukan kontrol sosial, memberi umpan balik, dan menjaga kesinambungan pola makan anak di rumah. Tanpa keterlibatan mereka, MBG mudah tereduksi menjadi rutinitas administratif yang kehilangan ruh.
Padahal, keberhasilan atau kegagalan MBG tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil interaksi kebijakan, anggaran, ilmu gizi, logistik, industri pangan, hingga peran orang tua. Dengan pengawalan yang kuat, MBG justru bisa menjadi kebijakan transformatif—memperbaiki sistem pangan nasional, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesehatan publik.
Syaratnya sederhana namun krusial: orientasi kesehatan jangka panjang harus mengalahkan logika kepraktisan dan kepentingan industri pangan ultra-proses. Tanpa kritik, pengawasan, dan transparansi, bom waktu akan terus berdetak tanpa suara. Kotak makan MBG mungkin tampak rapi dan seragam, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang berulang kali masuk ke dalam tubuh anak-anak kita.
Hari ini, melalui MBG, anak-anak mungkin kenyang. Namun masa depan tidak ditentukan oleh rasa kenyang sesaat, melainkan oleh apa yang perlahan membentuk darah, organ, dan metabolisme mereka. MBG bisa menjadi perisai kesehatan bangsa—atau sebaliknya, bom waktu yang meledak ketika generasi ini dewasa nanti. Pilihan itu sedang kita buat sekarang, lewat apa yang kita taruh di piring anak-anak kita.






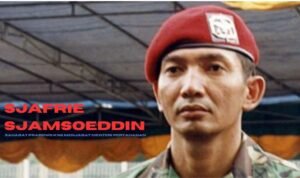

Komentar