✍🏻Risman Rachman
Kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh udah level desak Gubernur Aceh untuk nyuratin Presiden.
Tujuannya agar Prabowo segera menetapkan banjir Sumatera sebagai Bencana Nasonal.
Bukan cuma itu. Pengurus Pusat Taman Nasional Iskandar Muda bahkan menyutati Presiden RI untuk hal yang sama: penetapan status bencana nasional. Surat bertanggal 24 Desember 2025.
Padahal, semua pihak udah tahu ya, Pemerintah kekeh tidak akan menetapkan status bencana nasional.
Seskab Teddy pada (19/12/2025) lalu bahkan terkesan jengkel dengan usulan itu. Dia menegaskan bahwa Pemerintah sudah melakukan penangganan skala nasional, baik itu personil hingga anggaran, bahkan sejak hari pertama.
Sebelumnya, sikap yang kurang lebih sama juga sudah disampaikan mulai dari menteri, dewan, DPD yang mengarah kesamaan sikap dengan Presiden soal Pemerintah Mampu, tanpa perlu bantuan negara asing.
Presiden Prabowo sendiri yang menyatakan banyak negara yang ingin membantu. Namun, dirinya menegaskan jika Pemerintah mampu. “Kita mampu!”
Sikap Pemerintah itu jelas memicu spekulasi, dan bertebaranlah analisis dibalik penolakan penetapan status bencana nasional plus penolakan dukungan negara asing.
Saya tidak menolak dugaan yang ada. Sebab, semua punya alasan masing-masing. Terserah pembaca dalam mencernanya. Berikut saya sampaikan analisis saya.
1. Perangkap “Gengsi” Subjek di Panggung Dunia
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia sedang gencar membangun citra sebagai “Calon Kekuatan Besar Dunia”.
Pada 16 Desember lalu, saat berada di Papua Prabowo menyebut peluang Indonesia menjadi negara kelima atau keempat terbesar di dunia 10 atau 15 tahun ke depan.
Dengan citra diri dihadapan global seperti ini pemerintah jelas sangat berhati-hati dalam menjaga persepsi internasional.
Jika memilih menetapkan status “Bencana Nasional” secara otomatis akan memicu protokol bantuan internasional secara masif (G2G).
Bagi narasi Indonesia Mandiri, menerima bantuan asing dianggap sebagai pengakuan atas kelemahan domestik.
Karena itu mungkin, Pemerintah lebih memilih tampil sebagai subjek (pemberi bantuan, seperti dalam kasus Palestina) daripada menjadi objek (penerima bantuan), demi membuktikan bahwa “Negara Calon Raksasa” sanggup menyelesaikan urusannya sendiri.
2. Membentengi Kemenangan WTO dan “Diplomasi Sawit”
Alasan yang lebih pragmatis mungkin terletak pada komoditas emas hijau kita: Sawit. Setelah kemenangan Indonesia di WTO terkait biodiesel sawit pada Agustus 2025 lalu, pemerintah berada dalam posisi defensif untuk menjaga legitimasi tersebut.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga internasional dan LSM global sering kali menghubungkan bencana banjir/longsor di Sumatera dengan degradasi hutan akibat ekspansi lahan sawit.
Dengan menolak status bencana nasional dan membatasi akses asing (kecuali melalui jalur people-to-people yang terkontrol), pemerintah secara efektif melakukan gatekeeping informasi.
Tanpa pengawasan tim ahli dan jurnalis internasional, keterkaitan antara bencana ekologis dan industri sawit tetap menjadi “isu domestik” yang bisa diredam, sehingga tidak menjadi amunisi bagi Uni Eropa untuk menggugat balik di WTO.
3. Agenda Papua dan Narasi “Sawit adalah Pohon”
Keteguhan ini juga berkaitan erat dengan agenda strategis jangka panjang Presiden untuk melakukan ekspansi sawit besar-besaran di Papua. Dengan narasi bahwa “sawit adalah pohon” yang mampu menyerap CO2, dan pemerintah sedang mempromosikan swasembada BBM berbasis biofuel.
Jika bencana di Sumatera diakui sebagai kegagalan ekologis akibat tata kelola lahan, maka proyek di Papua akan menghadapi hambatan diplomasi yang luar biasa.
Oleh karena itu, kontrol terhadap konten dan narasi bencana di Sumatera seperti yang diwartakan Tempo dan dikeluhkan netizen adalah konsekuensi logis untuk mengamankan jalan bagi proyek strategis di Timur Indonesia.
Saya kira tiga analisis itu sudah cukup memadai ya, dan dalam konteks bencana Aceh bisa juga ditambah soal deforestasi yang merusak Kawasan Ekosistem Leuser.
Saya sih, untuk konteks Aceh, statusnya udah level bencana ekologi yang mengancam global. Saya kira, Uni Eropa pasti tahu karena mereka pasti sudah mendapat laporan langsung dari mitranya masing-masing di Aceh. Benarkannya?
(*)

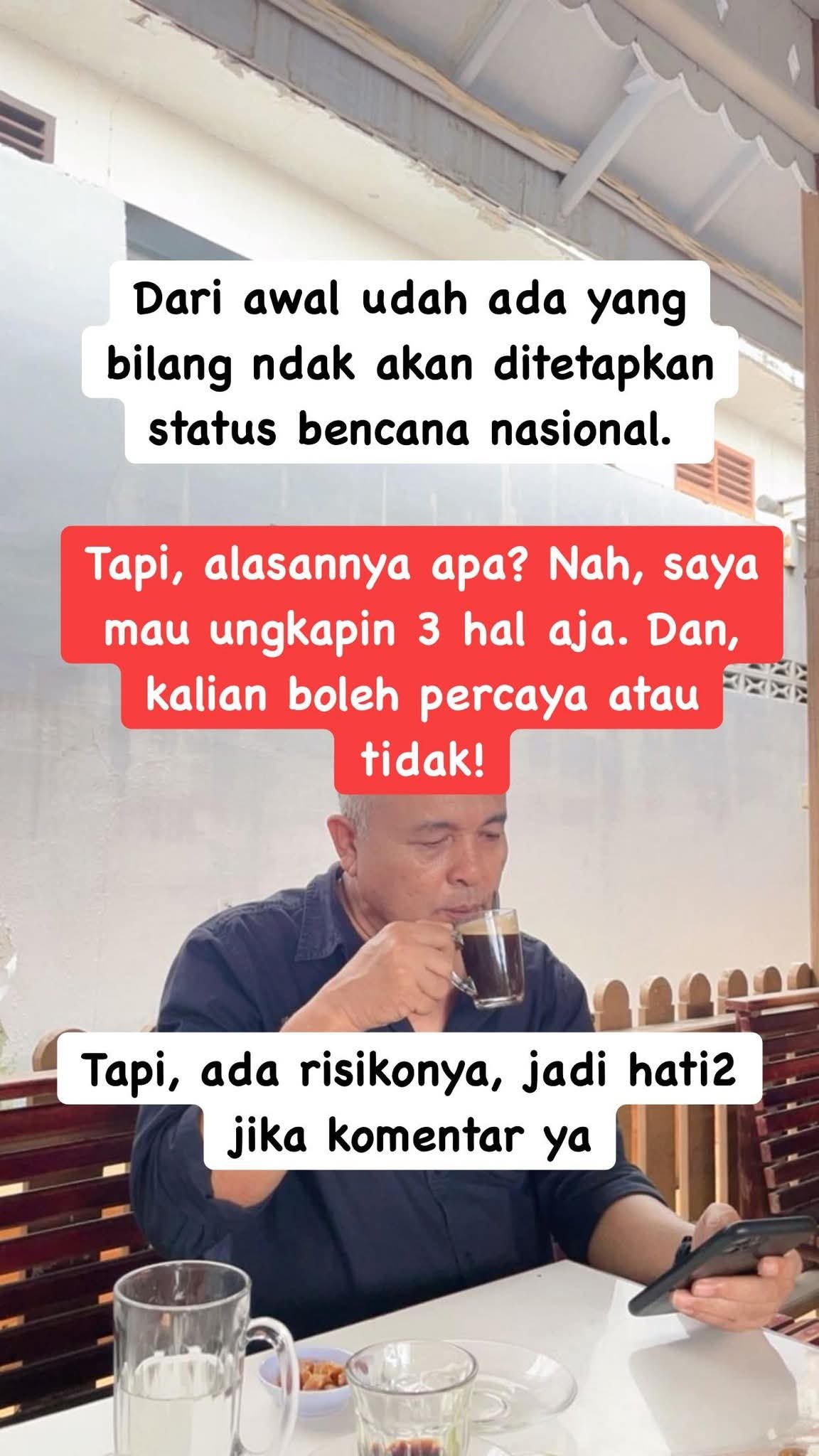






Komentar