Belakangan ini, kritik publik terhadap kinerja pemerintah tidak lagi semata soal hasil, melainkan soal cara kerja yang dipertontonkan. Banyak pejabat tampak sibuk membangun citra seolah bekerja keras, sementara dampak kebijakan di lapangan kerap dipertanyakan. Fenomena ini kemudian dilabeli publik dengan istilah narsistik, bukan sebagai diagnosis kejiwaan, melainkan sebagai kritik atas budaya kekuasaan yang terlalu gemar tampil.
Kasus Erick Thohir selama SEA Games 2025 menjadi contoh yang paling menonjol. Sepanjang perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara itu, Erick yang menjabat Menteri sekaligus Ketua PSSI terlihat konsisten hanya mengunggah capaian medali emas di akun media sosialnya. Medali perak dan perunggu nyaris tak mendapat ruang apresiasi serupa, seolah perjuangan atlet non emas tidak cukup layak untuk ditampilkan.
Padahal, dalam olahraga prestasi, medali perak dan perunggu tetap merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan proses panjang. Ketika narasi publik hanya dipusatkan pada emas, pesan yang tersampaikan bukan lagi semangat sportivitas, melainkan obsesi terhadap simbol kemenangan tertinggi. Prestasi dipersempit menjadi angka dan warna medali, bukan proses dan perjuangan kolektif.
Pola serupa juga tampak dalam penanganan bencana dan isu pangan. Dalam pemberitaan terkait bencana di Aceh dan Sumatera, publik disuguhi adegan pejabat memikul karung beras, berdiri di tengah lokasi bencana, dan berbicara panjang di depan kamera. Zulkifli Hasan misalnya tampil dalam sejumlah momen simbolik yang secara visual kuat, namun secara manajerial justru menimbulkan pertanyaan. Apakah kehadiran pejabat beserta rombongan dan kamera mempercepat distribusi bantuan, atau justru memperlambatnya.
Dalam manajemen bencana, yang dibutuhkan bukan aksi heroik di depan lensa, melainkan sistem logistik yang bekerja cepat, tepat, dan tanpa hambatan. Ketika bantuan harus menunggu seremoni, empati berubah menjadi pertunjukan.
Hal yang sama terlihat di sektor pangan. Aksi menteri pertanian yang membeli satu truk cabai dari petani Aceh lalu menggelar konferensi pers besar besaran mencerminkan ketimpangan antara skala tindakan dan skala narasi. Satu truk cabai tidak akan mengubah struktur pasar, tidak menstabilkan harga secara nasional, dan tidak menyelesaikan persoalan rantai distribusi. Namun publikasi yang menyertainya seolah menempatkan aksi tersebut sebagai solusi besar.
Di titik inilah kritik publik menemukan bentuknya. Yang dipersoalkan bukan ada atau tidaknya kerja, melainkan kecenderungan mengemas kerja kecil sebagai pencapaian besar. Kamera selalu lebih dulu hadir dibanding evaluasi dampak.
Sebagian masyarakat kemudian menyebut fenomena ini sebagai NPD kabinet. Istilah ini tentu tidak tepat jika dimaknai secara klinis. Namun sebagai metafora sosial dan politik, ia menggambarkan satu pola yang nyata, yaitu kebutuhan berlebihan akan pengakuan, validasi visual, dan sorotan publik. Negara dijalankan seperti panggung pertunjukan, di mana keberhasilan diukur dari seberapa sering tampil, bukan seberapa besar masalah diselesaikan.
Bahaya terbesar dari budaya pencitraan bukan sekadar kesan pamer. Bahayanya adalah kaburnya batas antara kerja nyata dan kerja visual. Ketika publik hanya disuguhi gambar dan narasi, ruang kritik mengecil. Kebijakan tidak lagi dinilai dari hasil, melainkan dari framing.
Padahal, dalam banyak kasus, pemerintahan yang efektif justru bekerja tanpa sorotan. Bantuan tiba tanpa seremoni. Kebijakan berjalan tanpa konferensi pers berlebihan. Hasilnya terasa, meski tidak selalu viral.
Jika kabinet Prabowo ingin dinilai serius dan berorientasi hasil, satu hal perlu dikoreksi. Kurangi panggung dan perkuat sistem. Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang paling terlihat bekerja, melainkan yang paling berdampak hasilnya.
Negara tidak kekurangan kamera.
Yang masih kurang adalah kebijakan yang benar benar bekerja.


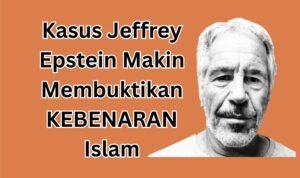





Komentar