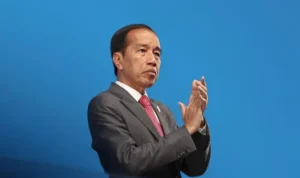MENGAPA NEGARA TAK BERANI MENYEBUTNYA BENCANA NASIONAL?
✍🏻Peter F. Gontha (Eks Dubes RI di Polandia)
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana besar. Korban jiwa jatuh, rumah hancur, alam rusak. Tapi negara memilih diam: tidak ada status bencana nasional.
Pertanyaannya sederhana: takut apa?
Di ruang publik beredar satu jawaban yang makin masuk akal:
jika bencana nasional ditetapkan, dunia akan masuk. Wartawan asing, lembaga internasional, relawan, bahkan institusi global akan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi.
Dan dari situ, pertanyaan berikutnya muncul:
Apakah ini murni bencana alam?
Atau hasil dari izin-izin yang salah, hutan yang ditebang, gunung yang dikeruk, sungai yang dihancurkan—selama bertahun-tahun, lintas rezim?
Nama-nama mulai disebut.
Bukan rakyat kecil.
Bukan petani.
Tapi mereka yang memberi dan menikmati izin.
Karena itulah status bencana nasional tidak dibuka.
Ironinya, Aceh kini menyatakan akan meminta bantuan UNDP dan UNESCO demi keselamatan rakyatnya. Negara menahan diri atas nama kedaulatan, tetapi daerah terpaksa membuka pintu karena warganya terancam.
Ini buah simalakama dari kebijakan yang setengah hati.
Jepang pernah mengalami tsunami besar tanpa deklarasi serupa. Tapi Jepang punya ekonomi kuat, institusi bersih, dan hampir tidak ada permainan izin. Indonesia? Kita tahu jawabannya.
Sampai hari ini, tak satu pun orang dimintai pertanggungjawaban hukum.
Tak ada pejabat.
Tak ada pemegang izin.
Tak ada korporasi.
Kalau hukum tak berjalan, bencana ini akan berulang.
Kalau negara terus diam, alam akan berbicara—dengan cara yang lebih kejam.
Menetapkan bencana nasional bukan soal administrasi.
Ini soal keberanian moral:
berani melindungi rakyat,
berani membuka kebenaran,
dan berani menegakkan hukum—meski menyakitkan.
Jika negara tak mau berkata jujur,
maka alam akan terus mengingatkan kita.