Siapa sangka, provinsi yang ditanami sawit hampir 1/2 luas wilayahnya justru merasa seperti pengemis di negerinya sendiri.
Riau, tanah yang dulu kaya oleh minyak, kini dikelilingi hamparan sawit raksasa seluas lebih dari 3,4 juta hektar, luasan yang lebih besar dari seluruh pulau Bali. Tapi di balik kejayaan itu, pertanyaannya sederhana, ke mana perginya uang sawit?
Dari angka resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Riau menjadi penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia. Tahun 2023, produksinya mencapai lebih dari 9 juta ton crude palm oil (CPO) menyumbang lebih dari 20% kebutuhan nasional. Jika dikalkulasikan secara kasar, dengan harga CPO berkisar Rp10.000 per kilogram, maka total nilai ekonominya bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Tapi angka-angka itu seolah hanya singgah sebentar di Riau, sebelum kembali pergi entah ke mana. Pendapatan daerah, alih-alih naik, justru semakin menipis. Dana yang dikucurkan kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten penghasil sawit jauh dari cukup untuk menutupi biaya infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan.
Dalam mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), Riau memang menerima bagian dari keuntungan sawit nasional. Namun jumlahnya sering tidak masuk akal. Pada tahun anggaran 2023, DBH sawit untuk Riau adalah sekitar Rp 391 miliar. Tapi di tahun berikutnya, jumlah itu justru anjlok menjadi hanya Rp 96 miliar, turun lebih dari 70 persen, padahal produksi tetap tinggi dan harga pasar relatif stabil. Bandingkan dengan pendapatan negara dari ekspor sawit nasional yang bisa mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Maka wajar kalau pemerintah daerah merasa bahwa Riau diperlakukan sekadar sebagai ladang, tanpa jaminan kesejahteraan bagi pemilik lahannya.
Ketimpangan itu makin mencolok ketika kita melihat kondisi masyarakat yang tinggal di tengah-tengah hamparan kebun. Desa-desa penghasil sawit masih banyak yang belum dialiri listrik, akses jalan tanah rusak, sekolah tidak memadai, bahkan tenaga kesehatan sering tak tersedia.
Padahal, hanya beberapa meter dari rumah warga, ada truk-truk tangki yang tiap hari mengangkut CPO bernilai miliaran rupiah.
Ironi itu semakin dalam ketika diketahui bahwa sebagian besar perkebunan sawit di Riau dikuasai oleh perusahaan besar, baik swasta nasional maupun asing. Mereka menguasai ribuan hingga puluhan ribu hektare lahan dalam satu konsesi, lengkap dengan pabrik dan infrastruktur internalnya.
Sebaliknya, petani kecil, baik plasma maupun swadaya, seringkali hanya mengelola satu atau dua hektare, dengan akses terbatas terhadap pupuk, bibit, dan harga jual yang kadang dikendalikan tengkulak.
Di sisi lain, pemerintah pusat menetapkan skema pembagian DBH sawit yang dianggap tidak adil. Besaran yang diterima daerah tidak sebanding dengan kontribusi produksi dan luas lahan. Malah sering kali, dana yang masuk ke kas daerah lebih sedikit dibandingkan biaya kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas truk sawit yang hilir-mudik tanpa henti. Misalnya, satu ruas jalan kabupaten di Rokan Hilir atau Pelalawan bisa rusak dalam waktu satu tahun karena dilewati kendaraan berat dari perusahaan. Tapi biaya perbaikannya tetap harus ditanggung pemerintah daerah, bukan perusahaan pemilik truk. Ini menjadi beban ganda bagi daerah: jadi penghasil utama, tapi menanggung kerusakan sendiri.
Belum selesai di situ, problem lain muncul dari tumpukan data perkebunan ilegal. Pemerintah Provinsi Riau mencatat, setidaknya ada lebih dari satu juta hektare kebun sawit yang tidak memiliki izin resmi atau berada di kawasan hutan. Kebun-kebun ini tidak membayar pajak, tidak terdata dalam sistem negara, tapi tetap berproduksi dan menghasilkan uang. Bahkan diduga sebagian dari kebun itu dikelola oleh korporasi besar atau jaringan mafia lahan yang punya koneksi kuat dengan oknum pejabat. Jika diasumsikan satu hektar kebun ilegal menghasilkan dua ton CPO per tahun, maka potensi produksi yang tidak tercatat bisa mencapai dua juta ton, atau setara dengan Rp20 triliun. Uang sebesar itu mengalir entah ke mana? Dan yang pasti, bukan ke kas daerah atau rakyat.
Kasus korupsi di sektor sawit juga bukan hal baru. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Tinggi Riau menahan tersangka kasus penggelapan dana pengelolaan kebun sawit seluas 500 hektar milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Aset daerah yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat justru dialihkan demi keuntungan pribadi. Negara dirugikan miliaran rupiah. Di Pelalawan, tiga pengurus koperasi petani sawit ditangkap karena membuat laporan fiktif untuk mencairkan dana peremajaan sawit rakyat (PSR). Mereka memalsukan data lahan dan petani, lalu mencairkan uang hingga Rp 1,25 miliar. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk mengganti tanaman tua menjadi sumber bancakan elite lokal.
Korupsi ini menunjukkan bahwa uang sawit tidak hanya bocor di pusat, tapi juga di tingkat bawah. Uang yang sudah sedikit, masih harus dibagi untuk orang-orang rakus yang memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya pengawasan. Bahkan program yang dirancang untuk membantu petani kecil pun berubah menjadi lahan korupsi. Tak heran jika akhirnya banyak petani swadaya yang enggan bergabung dengan koperasi atau program pemerintah. Mereka merasa lebih aman berdiri sendiri, meskipun tanpa perlindungan harga atau akses kredit yang layak.
Sementara itu, pemerintah pusat terus mendorong ekspansi sawit demi meningkatkan ekspor dan devisa. Tapi siapa yang menikmati devisa itu? Ketika minyak sawit diekspor ke India, China, atau Eropa, sebagian besar keuntungannya kembali ke perusahaan. Daerah penghasil seperti Riau hanya mendapat remah-remah, sedikit dari pajak kendaraan, sedikit dari PBB, dan sedikit dari DBH. Bahkan, industri hilir sawit, seperti pengolahan turunan, oleokimia, hingga biofuel, kebanyakan tidak dibangun di Riau. Nilai tambahnya dinikmati di provinsi lain, atau malah di luar negeri. Artinya, Riau hanya dijadikan ladang produksi bahan mentah. Seperti buruh tani yang diberi cangkul tapi tak pernah diajak ke meja makan.
Dalam situasi seperti ini, banyak tokoh dan akademisi lokal menyerukan agar sistem pembagian hasil sawit dirombak total. Mereka menuntut agar DBH ditingkatkan minimal 10 persen dari nilai ekspor CPO yang berasal dari Riau. Selain itu, perusahaan yang memiliki lahan di atas 5.000 hektare diwajibkan menyisihkan dana pembangunan desa, termasuk untuk jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Bahkan ada wacana agar provinsi penghasil sawit diberi kewenangan untuk mengenakan pajak daerah khusus, sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Tapi sampai hari ini, kebijakan semacam itu masih jauh dari kenyataan. Pemerintah pusat cenderung berhati-hati karena takut mengganggu investasi dan stabilitas industri.
Padahal, kalau dikelola dengan benar, sawit bisa menjadi berkah yang luar biasa. Banyak desa-desa di Riau yang dulunya terisolasi, kini punya jalan dan akses ekonomi karena kebun sawit. Beberapa petani plasma yang jujur dan rajin bekerja memang bisa menyekolahkan anak hingga ke universitas, bahkan membeli kendaraan dan membangun rumah permanen. Tapi jumlah mereka masih sedikit dibandingkan dengan petani swadaya yang hidup pas-pasan. Mereka bergantung pada harga sawit yang fluktuatif, biaya pupuk yang mahal, dan tidak punya jaringan pemasaran yang baik. Mereka inilah yang harusnya diberi prioritas dalam setiap program bantuan, bukan justru jadi korban dari proyek fiktif atau target pungutan liar.
Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan pada sawitnya, tapi pada struktur distribusi keuntungan yang timpang. Sawit tetap bisa jadi penopang ekonomi daerah, asal tidak semua keuntungannya disedot oleh pusat atau perusahaan besar. Dana bagi hasil yang adil, pengawasan yang ketat, dan transparansi penggunaan anggaran bisa membuat perubahan besar. Rakyat tidak menuntut kemewahan, tapi setidaknya jalan desa mereka tidak rusak, sekolah anaknya punya guru, dan puskesmas bisa melayani tanpa harus antri dua jam.
Dalam jangka panjang, perlu ada keberanian politik untuk membenahi sistem ini. Pemerintah daerah harus bersatu memperjuangkan haknya, bukan saling diam demi mempertahankan jatah proyek. Masyarakat sipil dan media lokal juga perlu lebih vokal mengawasi dana-dana yang mengalir dari sawit. Jangan sampai korupsi terus dibiarkan tumbuh di ladang yang katanya subur, sementara rakyat hanya bisa menatap sawit yang tak bisa dimakan.
Sebab yang menyakitkan bukan hanya ketika hasilnya tak dirasakan, tapi ketika orang-orang yang menyalahgunakannya justru hidup mewah di tengah kesulitan rakyat.
Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika kita sadar bahwa tanah yang kita pijak, pohon yang kita rawat, dan keringat yang kita keluarkan, rasanya tak pernah cukup kuat untuk membebaskan kita dari kemiskinan. Maka sudah waktunya sawit bukan hanya menjadi simbol kejayaan, tapi juga keadilan. Sebab keadilan, sama seperti sawit, seharusnya bisa tumbuh di mana pun tanahnya subur. Termasuk di Riau.
(fb Pecah Telur)



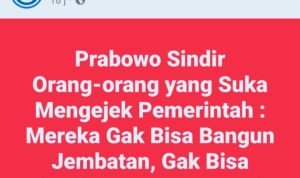




Komentar