Satu dekade pemerintahan Jokowi ditandai dengan geliat pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan tentu saja deretan bandara baru menjadi simbol ambisi membuka konektivitas Nusantara. Dalam periode 2014 sampai 2024, pemerintah dan BUMN membangun sekitar 27 bandara baru, belum termasuk proyek rehabilitasi dan perluasan puluhan bandara lainnya. Tetapi setelah gegap gempita pembangunan mereda, muncul pertanyaan besar: apakah semuanya benar-benar dibutuhkan?
Jika menelusuri berbagai laporan anggaran proyek dari APBN, penyertaan modal negara dan investasi BUMN seperti Angkasa Pura, estimasi kasar biaya membangun 27 bandara tersebut berada di kisaran 14 sampai 20 triliun rupiah. Angka ini merupakan akumulasi dari proyek yang tingkat investasinya berbeda-beda. Ada bandara kecil di perbatasan yang hanya menghabiskan ratusan miliar rupiah, namun ada juga yang menyerap triliunan rupiah seperti Bandara Kertajati dan Yogyakarta International Airport.
Masalahnya, tidak semua bandara berjalan sesuai harapan. Sebagian memang hidup dan tumbuh seperti YIA atau Bandara Sibolga yang terus mencatat kenaikan penumpang. Namun cukup banyak bandara lain yang kondisinya sepi, minim penerbangan, bahkan cenderung menjadi monumen sunyi dari ambisi pembangunan infrastruktur.
Bandara seperti Ngloram, Tambelan, Morowali dan Siau misalnya, mencatat pergerakan penumpang yang sangat rendah. Ada bandara yang hanya menerima pesawat kecil beberapa kali dalam sebulan, ada juga yang rute komersialnya terputus sama sekali. Bahkan sebagian sempat berhenti beroperasi sementara karena tidak ada maskapai yang berminat terbang. Ketika satu bandara membutuhkan subsidi operasional belasan miliar rupiah per tahun agar tetap hidup, dapat dibayangkan betapa beratnya beban negara untuk menjaga puluhan bandara yang mengalami hal serupa.
Pertanyaannya, apakah persoalan ini lahir dari proses perencanaan yang terburu-buru, atau karena obsesi politik bahwa pembangunan fisik selalu terlihat sebagai prestasi?
Pembangunan infrastruktur seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata dan potensi ekonomi jangka panjang. Ketika konektivitas udara dibangun tanpa ekosistem ekonomi yang mendukung seperti industri, pariwisata atau logistik yang mapan, hasil akhirnya mudah ditebak. Bandara berdiri, tetapi pesawat tidak datang.
Kini setelah lebih dari 14 triliun rupiah terserap, publik mulai menuntut evaluasi. Bukan untuk menolak pembangunan, tetapi agar pemanfaatan anggaran negara lebih tepat sasaran. Indonesia tidak kekurangan bandara. Yang kita perlukan adalah bandara yang benar-benar berfungsi. Bukan hanya megah secara fisik, tetapi hidup, terisi dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.



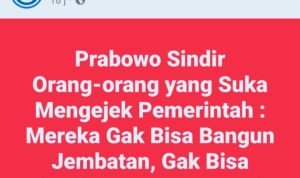




Komentar