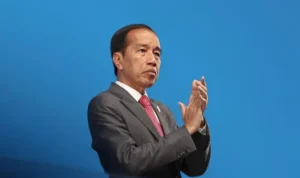✍🏻Erizeli Jely Bandaro
Pola pembangunan Indonesia terlalu konsisten untuk diabaikan. Ia selalu dimulai dengan janji tentang ketahanan pangan, kemandirian energi, lapangan kerja dan hampir selalu berakhir dengan hasil yang sama: hutan hilang, tanah terkonsentrasi, dan kekayaan mengalir ke segelintir tangan.
Sumatera telah membayar mahal. Dalam dua dekade terakhir, pulau ini kehilangan lebih dari 4 juta hektare hutan akibat ekspansi sawit, pertambangan, dan konsesi berbasis rente. Dampaknya nyata: kabut asap kronis, konflik agraria, banjir, longsor, serta degradasi sosial yang terus berulang. Namun setelah hutan menipis, negara tidak berhenti? ia berpindah.
Kini, Papua disebut.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan harapan agar Papua ditanami kelapa sawit demi swasembada energi dan produksi BBM berbasis sawit. Secara teknokratis, narasi ini terdengar rasional. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pola lama yang kembali diulang di wilayah yang berbeda.
Papua bukan Sumatera. Ia adalah benteng ekologi terakhir Indonesia, dengan sekitar 80 persen wilayahnya masih tertutup hutan alam, termasuk salah satu kawasan hutan primer terbesar di Asia Pasifik. Menjadikannya kebun sawit berarti mengulang kesalahan lama di ruang yang jauh lebih rapuh dan tidak tergantikan.
Sawit adalah komoditas yang efisien, bukan hanya secara agronomis, tetapi secara politis. Ia membutuhkan konsesi luas, modal besar, dan perlindungan kebijakan. Artinya, secara struktural ia menguntungkan konglomerat, bukan masyarakat adat. Pengalaman panjang menunjukkan: ketika negara berbicara tentang sawit, kepemilikan hampir selalu berakhir di tangan grup besar, sementara masyarakat lokal kehilangan ruang hidup.
Pertanyaan mendasarnya sederhana adalah:
Apakah sawit benar-benar solusi energi, atau hanya ekspansi ekstraktif dengan wajah baru?
BBM berbasis sawit tetap bergantung pada harga CPO global, subsidi kebijakan, dan perluasan lahan. Ketika harga turun, ekspansi kembali dijadikan jalan keluar. Ini bukan transisi energi, melainkan perpanjangan ketergantungan komoditas.
Masalahnya bukan sekadar ekologi. Kegagalan model pembangunan masalalu seharusnya jadi pelajaran. Kini kita mengalami defisit fiskal dan beban utang yang terus membesar. Bahkan worldbank menyebut lebih separuh rakyat tetap miskin.
Model ini terbukti gagal menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan kemakmuran bagi semua . Yang kaya tetap konglomerat, negara tetap terjebak defisit, dan kerusakan lingkungan diwariskan ke generasi berikutnya.
Papua bukan halaman kosong di peta investasi. Ia adalah ujian terakhir: apakah negara mampu belajar dari kegagalan Sumatera, atau kembali mengulangnya, dengan hutan sebagai korban dan oligarki sebagai pemenang.
Pembangunan yang miskin kreativitas dan inovasi, lalu memilih merusak ekologi, bukanlah kemajuan. Itu hanya cara lama yang gagal—diulang di tempat baru.
(*)