Ketika Pejabat Zalim dan Korup Berkolaborasi dengan Pengusaha Bejat dan Rakus
✍🏻Hafidin Achmad Luthfie
Banjir bandang yang meluluhlantakkan Sumatera bukan sekadar luapan air yang tiba-tiba datang dari langit. Ia adalah jeritan bumi—jeritan yang sudah lama disumpal, dipaksa diam oleh gergaji, alat berat, dan izin-izin yang diteken dengan tangan kotor. Ketika jeritan itu akhirnya pecah, ia berubah menjadi luka besar yang merambat dari desa ke desa: merobohkan rumah, menghanyutkan manusia, memusnahkan ternak, bahkan memaksa hewan-hewan hutan meninggalkan tempat tinggalnya.
Hutan-hutan yang dulu menjadi tameng tanah kini habis dibabat. Lereng-lereng yang dulu kokoh kini runtuh seperti tubuh yang kehilangan tulang. Sungai-sungai yang dulu mengalirkan kehidupan kini menjelma arus kematian.

Namun di tengah derita itu, kita mendengar kalimat-kalimat yang lebih memedihkan dari banjir itu sendiri: pejabat yang berkata, “Ini bukan bencana nasional.”
Seakan ribuan rumah yang hilang belum cukup, seakan hilangnya nyawa manusia belum pantas menggugah empati mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
Lalu keluar pernyataan yang lebih menusuk lagi: kayu-kayu raksasa yang berserakan di aliran banjir disebut “tumbang alami.”
Padahal foto, video, dan saksi mata menunjukkan kebenaran yang tak bisa disembunyikan: itu adalah jejak eksploitasi, jejak perusahaan yang menggasak hutan, jejak izin yang dijual murah, jejak kerakusan yang dilegalkan oleh tangan-tangan yang seharusnya menjaga rakyat.
Belum cukup sampai di situ, muncul suara lain yang meremehkan kerusakan hutan, seolah deforestasi tak ada hubungannya dengan banjir bandang. Mereka lupa—atau sengaja melupakan—bahwa hutan adalah pelindung pertama bumi. Ketika ia dirusak, banjir hanyalah konsekuensi yang berjalan menurut hukum alam. Tidak ada yang “tiba-tiba.” Yang tiba-tiba hanyalah pengakuan pejabat yang sibuk menutupi jejak dosa kebijakan mereka.
Ironinya, ketika kekuasaan menyangkal, bumi justru bersaksi. Banjir membawa naik kayu-kayu yang dicuri, lumpur yang dipermalukan, pohon-pohon yang dipaksa tumbang. Semua itu adalah bukti telanjang bahwa kerusakan ini buatan manusia, bukan takdir yang jatuh dari langit.
Di tengah tangis warga yang belum kering, kita teringat pemimpin yang pernah menjadi standar emas amanah publik. Umar bin Khaththab berkata:
“Seandainya seekor kambing mati terperosok di pinggir Sungai Eufrat, aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku pada hari kiamat.”
Beliau takut ditanya tentang seekor kambing.
Sementara di negeri ini, nyawa manusia melayang, hutan dimutilasi, sungai diperkosa, dan hewan-hewan kehilangan rumahnya—namun tidak ada secuil ketakutan dalam dada para pemegang kuasa.
Betapa jauh kita meluncur dari teladan kepemimpinan itu.
Betapa jauh kita dari rasa takut kepada Allah, Penguasa semua makhluk.
Dan betapa perih melihat rakyat dipukul bencana, sementara pejabat sibuk menyusun alasan dan narasi pembenaran, bukan solusi.
Banjir ini bukan hanya bencana alam—ia adalah aib moral. Aib dari kekuasaan yang kehilangan hati. Aib dari pengusaha yang hanya mengenal untung. Aib dari kebijakan yang mengizinkan alam dibantai atas nama “pembangunan.”
Semoga masih ada ruang dalam hati mereka yang diberi amanah untuk melihat kenyataan ini, bukan menutupinya. Sebab jika manusia terus menolak mengakui kesalahannya, bumi akan terus membuka bukti-buktinya—sampai kita belajar, atau sampai semuanya benar-benar terlambat.




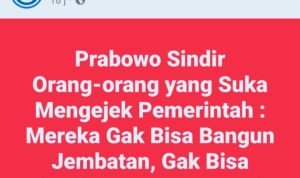




Komentar