✍️ Catatan Agus M. Maksum
Di Amerika, seorang anak muda imigran Muslim bernama Zohran Mamdani baru saja menulis ulang sejarah.
Ia menembus semua yang disebut impossible:
- Melawan dinasti politik
- Menantang presiden yang berkuasa
- Mendukung Palestina di tengah kota dengan komunitas Yahudi terbesar di dunia
- dan menang.
Orang-orang di sini bertanya: kok bisa?
Jawabnya sederhana: karena lembaga pemilunya masih bekerja.
Karena mesin demokrasinya masih hidup.
Masih bisa dipercaya.
Masih bisa kalah—dan menerima kalah.
Masih bisa menang—tanpa harus bersekongkol.
Itu saja.
Sederhana, tapi mahal.
Di Amerika, suara rakyat masih dihitung.
Di Indonesia, suara rakyat masih… dihitung-hitung.
Kalau di New York, yang mustahil bisa terjadi karena sistemnya tegak,
di sini, yang mustahil justru adalah keadilan dalam hitungannya.
Kita sering mengira, untuk menang pemilu, cukup punya visi, program, dan rakyat.
Padahal di Indonesia, langkah pertama bukan menguasai rakyat.
Langkah pertama adalah menguasai lembaga pemilu.
Itulah realita getir kita.
Bukan siapa yang paling dicintai rakyat yang menang,
tapi siapa yang paling duluan masuk ke ruang server.
Di sini, penghitungan bukan lagi tentang suara, tapi tentang data.
Dan data—seperti semua hal di negeri ini—bisa dinegosiasikan.
Maka muncullah guyonan internasional yang pahit tapi lucu:
“Di Indonesia, hasil pemilu sudah bisa diumumkan… bahkan sebelum pemilu terjadi.”
Guyonan itu tidak sepenuhnya keliru.
Kita tertawa—karena kita tahu itu benar.
Dan saat Mamdani bisa menang dengan jujur di jantung kapitalisme dunia,
Kita di jantung demokrasi Asia malah sibuk mencari jalan pintas untuk mengamankan kemenangan.
Lucunya, kita menamainya rekap cepat.
Cepat sekali, sampai-sampai prosesnya tak sempat diawasi.
Kita senang bicara tentang keajaiban demokrasi.
Padahal yang kita jalankan adalah sulap elektoral.
Yang satu memenangkan hati rakyat.
Yang satu memenangkan rapat pleno.
Jadi, kalau Anda bertanya:
Apakah mungkin seorang Mamdani lahir di Indonesia?
Jawabannya—dengan getir tapi jujur—
Tidak, sebelum KPU kembali menjadi lembaga, bukan alat.
Selama suara rakyat bisa diatur dari ruang rapat,
Selama hasil pemilu bisa disetting dari meja kekuasaan,
Maka yang mustahil di Indonesia bukanlah menang seperti Mamdani —
Tapi menang tanpa restu oligarki
Sebab di negeri ini,
Yang dihitung bukan lagi suara rakyat…
Tapi seberapa patuh lembaga pemilu pada skenario.
Dan selama itu belum berubah,
Jangan mimpi ada “Mamdani” lahir di sini.
Yang lahir hanyalah pemenang yang sudah ditentukan sebelum rakyat memilih.



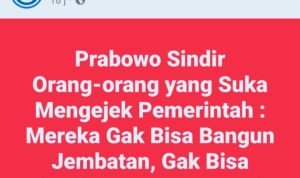




Komentar