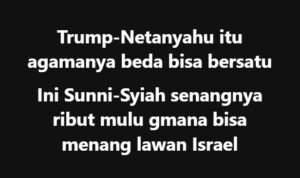✍🏻Erizeli Bandaro
Ketika publik dunia melihat keberhasilan Amerika Serikat dalam menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, di Caracas, banyak yang tergugah oleh gambaran tentang “kekuatan tak terbatas” Washington.
Namun menangkap seorang presiden dalam sebuah operasi militer atau penegakKan hukum yang sukses, bukanlah hal yang sama dengan menguasai politik sebuah negara secara komprehensif. Ini adalah distingsi penting dalam studi hubungan internasional dan political risk.
Makanya jangan kaget bila paska penangkapan Maduro, Presiden Donald Trump mengundang para CEO perusahaan minyak besar ke Gedung Putih. Minta mereka berinvestasi ratusan miliar dolar di sektor Minyak di Venezuela, namun respons yang muncul justru dingin dan skeptis. Mengapa? Darren Woods, CEO ExxonMobil secara terbuka menyebut bahwa Venezuela saat ini “uninvestable” karena kerangka hukum dan komersialnya belum siap untuk memberikan kepastian kontraktual kepada investor asing.
Para TNC Amerika itu punya pengalaman pahit tahun 2006 ketika asset mereka dinasionalisasi oleh rezim Hugo Chávez. AS hanya bisa melawan dengan sanksi ekonomi terhadap Venezuela. Jadi ya bisnis itu selalu akal sehat. Selagi perubahan politik di Venezuela tidak terjadi dan stabiitas politik tidak menjamin, ya bukan pilihan yang rasional untuk invest. Engga ada urusan walau Venezueala pemilik SDA minyak terbesar di dunia. Bahkan walau Trump menjamin perubahan politik di Venezuela seperti yang dia mau. Investor ignore saja. Karena mereka tahu, itu hanya pidato.
Mengapa? ini bukan sekedar urusan domestic. Selama sekian dekade baik China, Rusia maupun Iran telah menanam kepentingan ekonomi, keamanan, dan simbolik dalam hubungan mereka dengan Caracas. Jika Washington ingin mengubah rezim atau sistem politik Venezuela secara fundamental, ia harus menghadapi jaringan proxy Rusia, China dan Iran di Venezuela. Para proxy ini akan jadi mesin efektif melumpuhkan rezim boneka AS. Sebagaimana dicatat oleh Graham Allison dalam konsep great power competition.
Sejarah kekuatan militer AS penuh dengan contoh di mana kemenangan militer — bahkan dalam skala besar — tidak otomatis menghasilkan dominasi politik jangka panjang. Perang Vietnam dan Afganistan adalah ilustrasi klasik: meskipun AS menang dalam banyak pertempuran militer, tujuan politik jangka panjang tidak tercapai.
Dalam teori political risk dan ekonomi institusional yang dikembangkan Douglass North, yang membuat perubahan politik dapat dipercaya bukan rezim baru sebagai boneka, melainkan institusi yang menopang perubahan tersebut. Dimana sistem hukum yang bisa dipercaya, fungsi pemerintahan yang konsisten, dan birokrasi yang tidak mudah berubah arah dengan setiap ganti presiden atau tekanan eksternal. North menekankan bahwa tanpa institusi yang stabil dan konsisten, modifikasi rezim akan selalu dianggap terasionalisasi semu, bukan transformasi yang bankable dalam istilah finansial.
Kasus Iran
Jika Amerika Serikat saja mengalami kesulitan mengubah ranah politik domestik Venezuela meski mampu melakukan operasi koersif yang “sukses” pada level individu (menangkap Presidennya), maka upaya serupa terhadap Iran akan jauh lebih sulit, mahal, dan tidak pasti.
Ini bukan sekadar soal kapasitas militer, melainkan soal kompleksitas institusional, kohesi sosial-politik, dan struktur aliansi yang membentuk daya tahan negara modern.
Venezuela menunjukkan bahwa perubahan aktor di puncak tidak otomatis menghasilkan konsolidasi institusional; negara bisa tetap eksis, elite tetap solid, dan kepastian hukum tetap tidak terbentuk, sehingga modal besar tetap menahan diri. Logika inilah yang membuat analisis “serangan cepat sama dengan kemenangan politik” menjadi simplifikasi yang tidak tahan uji.
Iran, berbeda dari Venezuela, merupakan pemain kunci dalam geopolitik energi karena kedekatannya dengan chokepoint paling kritis di dunia: Selat Hormuz.

Pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz rata-rata sekitar 20 juta barel per hari, setara kira-kira 20% konsumsi global petroleum liquids.
International Energy Agency juga menekankan bahwa sekitar seperempat perdagangan minyak dunia via laut melintasi jalur ini, sementara opsi bypass bersifat terbatas.
Sehingga gangguan kecil pun berpotensi menciptakan guncangan harga dan pasokan secara global.
Artinya, risiko serangan terhadap Iran tidak hanya militer, tetapi juga risiko sistemik terhadap pasar energi, inflasi, dan stabilitas makro ekonomi global.
Dari sisi keamanan, Iran bukan sekadar negara berdaulat biasa; ia mengembangkan kapabilitas militer asimetris yang secara eksplisit menempatkan penguasaan medan maritim (termasuk strategi gangguan di Selat Hormuz) sebagai bagian utama doktrin defensifnya.
Evaluasi sektor energi pun mencatat bahwa wacana “penutupan Hormuz” selalu menjadi variabel risiko yang diperhitungkan pasar karena dapat mengancam setidaknya seperlima pasokan minyak dunia. Dalam kerangka political economy of war, kemampuan asimetris seperti ini membuat perang tidak berhenti pada target militer, tetapi menyebar ke biaya ekonomi yang luas.
Di atas itu, Iran beroperasi dalam ekosistem proxy dan jaringan regional yang membuat eskalasi cenderung menyebar lintas wilayah, bukan terkunci pada satu front. Literatur tentang dinamika Teluk Persi menempatkan konflik proksi (Yaman, Suriah, Irak, Lebanon) sebagai pola kompetisi yang nyata dan berulang, sehingga setiap aksi militer besar terhadap Iran memiliki probabilitas tinggi memicu spillover regional.
Kompleksitas tersebut semakin berat karena Iran tidak berdiri sendirian dalam struktur geopolitik. Hubungan Iran–Rusia mengalami pendalaman formal melalui Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani pada 2025—yang, meski tidak identik dengan pakta pertahanan mutual, tetap memperkuat koordinasi politik dan keamanan.
Di saat yang sama, analisis kebijakan juga mencatat bahwa Tehran memperkuat orientasi “eastward pivot” ke Rusia dan China untuk menahan tekanan sanksi dan meningkatkan daya gentarnya, meski derajat dukungan kedua negara itu tidak selalu tanpa syarat. Konsekuensinya, serangan terhadap Iran bukan sekadar duel bilateral; ia berpotensi memicu kalkulus balasan dan penguncian posisi kekuatan besar lainnya—minimal pada level diplomasi, sanksi-balas-sanksi, dan pengaruh di pasar energi.
Karena itu, opsi militer terhadap Iran adalah skenario berbiaya tinggi dan berketidakpastian tinggi. Bukan hanya karena faktor militer, tetapi karena kombinasi: (1) chokepoint energi global, (2) strategi asimetris, (3) jaringan proksi regional, dan (4) kedalaman kompetisi kekuatan besar.
Pada sistem internasional yang multipolar dan rapuh, kalkulasi rasional Washington dan sekutunya hampir pasti menempatkan opsi militer sebagai pilihan terakhir, bukan respons primer.
(*)