Bila Gubernur Gagal Paham
Oleh: Hamid Awaludin
Mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia
Pagi 15 Agustus 2005, di sebuah gedung di jantung kota Helsinki, Finlandia, dunia menatap ke arah peristiwa bersejarah: penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Setelah hampir tiga dekade konflik bersenjata, pagi itu menjadi saksi berakhirnya pertikaian panjang di Tanah Rencong. Dentuman senjata antara TNI dan GAM dibungkam, dan sebuah lembar sejarah baru ditulis.
Sebagai ketua tim perunding pemerintah, saya menandatangani kesepakatan itu sambil menyampaikan pesan:
“Mulai hari ini, garis pemisah antara ‘kami’ dan ‘mereka’ harus dihapuskan. Kita hanya punya satu garis — yakni kita. Mari kita rajut kembali perbedaan masa lalu menjadi sulaman indah yang bernama persatuan.”
Saya menutup pidato dengan peribahasa Aceh yang sarat makna:
“Pat ujen han pirang, pat prang tan reda” — tiada hujan yang tak berhenti, tiada perang yang tak berakhir.
Dua puluh tahun kemudian, kenangan itu kembali menyeruak di benak saya. Pemicunya adalah kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menghentikan kendaraan berpelat Aceh ketika melintas di wilayahnya, dengan alasan ingin memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah itu, secara simbolik, menghidupkan kembali sekat “kami” dan “mereka” yang telah kita kubur dalam perjanjian damai Helsinki.
Sebuah Keteledoran Berbahaya
Tindakan tersebut bukan hanya keliru secara etika kebangsaan, tetapi juga menyalahi prinsip dasar “Persatuan Indonesia” — sila ketiga Pancasila. Kebijakan itu berpotensi menyalakan bara konflik lama dan merusak harmoni antarwilayah.
Dari sisi hukum, Gubernur Bobby Nasution jelas keliru memahami kewenangannya.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan, penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan wewenang kepolisian, bukan gubernur.
Selama kewajiban pajak kendaraan telah dipenuhi, pelat nomor mana pun — termasuk dari Aceh — berhak melintas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor dibayarkan sesuai domisili pemiliknya. Artinya, jika pemilik kendaraan berdomisili di Aceh, maka pajak dibayarkan di Aceh — bukan di Sumatera Utara.
Memaksa pemilik kendaraan Aceh membayar pajak di luar domisilinya adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Pendapatan asli daerah tidak boleh diraih dengan cara menimbulkan dikotomi dan ketegangan antarprovinsi.
Mengulang Luka Lama
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengingatkan, gubernur dilarang mengambil kebijakan yang berpotensi mengganggu hubungan harmonis antarwilayah.
Kebijakan penghentian kendaraan berpelat Aceh di Sumatera Utara jelas melukai perasaan masyarakat Aceh dan berpotensi menumbuhkan kembali fanatisme kedaerahan yang berbahaya bagi persatuan nasional.
Apakah ini yang kita kehendaki?
Apalagi, luka hati masyarakat Aceh belum sepenuhnya pulih setelah sempat muncul polemik terkait klaim Gubernur Bobby terhadap empat pulau yang sejak dahulu masuk wilayah Aceh. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan agar isu tersebut tidak menimbulkan ketegangan baru.
Jangan Korbankan Akal Sehat
Demi alasan peningkatan PAD, akal sehat tidak boleh dikorbankan. Kebijakan semacam ini hanya menumbuhkan rasa ketidakadilan dan memupuk ketersinggungan yang berbahaya.
Padahal, secara ekonomi, Aceh dan Sumatera Utara saling bergantung. Truk-truk dari Aceh mengangkut hasil bumi ke Sumut, sementara barang-barang dari Sumut pun banyak dikirim ke Aceh. Hubungan itu bersifat mutual benefit.
Tanpa lalu lintas ekonomi antarprovinsi ini, Sumut justru bisa merugi. Maka, pantas jika publik bertanya: apa sebenarnya yang ingin dicari Pak Gubernur?
Teguran untuk Pemimpin yang Lupa Diri
Menteri Dalam Negeri, sesuai kewenangannya, patut turun tangan untuk menegur, bahkan memberikan sanksi bila perlu, terhadap kepala daerah yang bertindak melampaui batas kewenangannya.
Gubernur bukan hanya kepala daerah otonom, tetapi juga perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka, setiap kebijakan harus selaras dengan semangat persatuan nasional.
Sebagaimana lagu lama yang penuh makna peringatan:
“Sudah kubilang, jangan dekati api yang membara. Jangan sampai terbakar nanti.”
Artikel ini merupakan opini pribadi penulis.
Sumber asli: Kompas.com, 5 Oktober 2025, dengan judul “Bila Gubernur Gagal Paham”



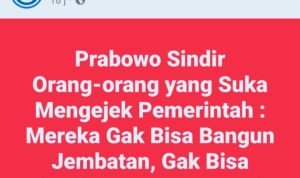




Komentar