Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 yang diteken Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, pada 12 Februari 2026.
Secara administratif, tak ada yang janggal. Pemenang lelang wajib membayar harga dasar data sebagai penerimaan negara bukan pajak dan menempatkan komitmen eksplorasi di bank BUMN. Jika gagal memenuhi kewajiban, status pemenang dapat gugur dan digantikan peringkat berikutnya. Prosedur tampak rapi.
Namun persoalan menjadi sensitif ketika menilik latar belakang perusahaan tersebut. PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan afiliasi dari Ormat Technologies Inc., perusahaan energi panas bumi yang berdiri di Yavne, Israel, pada 1965. Ormat tercatat di Bursa Efek Tel Aviv sejak 1991 dan melantai di New York Stock Exchange pada 2004 dengan kode ORA. Perusahaan ini telah membangun dan mengoperasikan proyek panas bumi di berbagai negara.
Di Indonesia, Ormat sebelumnya terlibat dalam proyek PLTP Ijen di Jawa Timur dan proyek PLTP Sarulla di Sumatera Utara bersama sejumlah mitra internasional. Artinya, keterlibatan perusahaan ini bukan hal baru dalam sektor energi nasional.
Tetapi konteks geopolitik membuat keputusan ini sulit dipandang sekadar bisnis. Di tengah memanasnya konflik Israel–Palestina dan berbagai tudingan pelanggaran kemanusiaan di Gaza, muncul pertanyaan etis: apakah aliran keuntungan dari proyek strategis di Indonesia secara tidak langsung memperkuat entitas bisnis yang berbasis di Israel?
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa keputusan ini bisa berdampak pada posisi moral Indonesia di mata internasional. Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Maka ketika proyek strategis energi justru dimenangkan perusahaan yang berakar dari Israel, wajar jika publik bertanya: di mana garis tegas antara kepentingan bisnis dan komitmen politik luar negeri?
Pemerintah mungkin berargumen bahwa investasi energi terbarukan harus dinilai secara profesional dan teknokratis. Panas bumi adalah bagian penting transisi energi. Namun di ruang publik, isu ini tak berhenti pada kalkulasi megawatt dan investasi. Ia menyentuh sensitivitas solidaritas, sikap politik, dan konsistensi moral.
Hingga kini, pihak ESDM belum memberikan penjelasan rinci terkait pertimbangan geopolitik atas penetapan tersebut. Tanpa transparansi yang memadai, keputusan ini berisiko dipersepsikan sebagai langkah yang abai terhadap sentimen publik atau lebih jauh lagi, dianggap kontradiktif dengan sikap resmi Indonesia terhadap konflik di Gaza.
Apakah ini murni soal energi, atau ada pesan lain yang tak terucap? Publik berhak mendapat jawaban yang lebih terang.



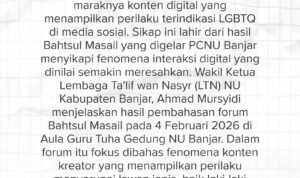




antek-antek aseng asing ..